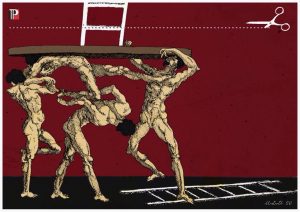Ilustrasi: Flickr/Lanpernas
NANCY Fraser adalah profesor filsafat dan politik pada Henry dan Louise A. Loeb di New School for Social Research di New York, yang bekerja di bidang teori sosial, politik, dan feminis. Dia telah menulis beberapa buku, seperti Cannibal Capitalism: How Our System Is Devouring Democracy, Care, and the Planet—and What We Can Do About It. Dalam wawancara mendalam ini, Fraser berbincang dengan Federico Fuentes untuk LINKS International Journal of Socialist Renewal tentang bagaimana transfer kekayaan alam dan perawatan masuk dalam imperialisme modern, peran ekspropriasi dalam akumulasi modal, dan sifat batas inti-periferi yang semakin kabur di bawah kapitalisme yang terfinansialisasi.
Artikel ini diterjemahkan dan diterbitkan ulang di sini untuk kepentingan pembangunan gerakan anti-imperialisme di Indonesia.
Federico Fuentes (FF): Selama abad terakhir, istilah imperialisme telah digunakan untuk mendefinisikan situasi yang berbeda dan, pada beberapa kesempatan, digantikan oleh konsep-konsep seperti globalisasi dan hegemoni. Apakah konsep imperialisme tetap valid, dan jika ya, bagaimana Anda mendefinisikannya?
Nancy Fraser (NF): Istilah imperialisme, menurut saya, tetap esensial dan saya tidak sepakat jika menggantinya dengan konsep lain. Misalnya, menggantinya dengan istilah yang populer seperti globalisasi. Jika yang dimaksud dengan globalisasi hanyalah bahwa kebijakan industri dan ekonomi nasional kini dianggap telah usang, serta munculnya neoliberalisme dan dominasi kekuasaan kapitalis elite melalui agenda perdagangan bebas, maka itu bisa diterima. Namun, imperialisme berbicara tentang hal yang berbeda.
Konsep hegemoni juga penting dalam kajian geopolitik. Secara umum, hegemoni merujuk pada peran yang dimainkan oleh kekuatan imperialis (atau blok kekuatan) dalam membentuk dan mengatur tatanan ruang global untuk memfasilitasi ekstraksi imperialis. Namun, ini merujuk pada organisasi politik ruang global. Lagi-lagi, ini berbeda dari imperialisme walaupun keduanya saling terkait, tetapi keduanya bukanlah hal yang sama.
Saat ini juga populer istilah seperti kolonialitas dan dekolonialitas. Wacana ini berusaha menunjukkan bahwa meskipun kolonialisme langsung telah berakhir, hierarki kolonial dalam nilai budaya tetap ada. Ide ini sendiri tidak masalah. Namun, ketika digunakan untuk menggantikan konsep imperialisme—seperti yang sering terjadi—hal ini akhirnya menempatkan isu kapitalisme global atau imperial pada posisi yang kurang prioritas atau menjadi terpinggirkan. Padahal, justru di situlah analisis kita seharusnya dimulai.
Oleh karena itu, saya sangat mendukung penggunaan istilah imperialisme, meskipun menurut kita perlu memperluas dan memperdalam pemahamannya. Dalam pengertian ekonomi yang ketat, imperialisme merujuk pada proses transfer atau perampasan nilai (extraction of value) oleh kekuatan tertentu dari wilayah-wilayah yang dianggap sebagai wilayah pinggiran. Namun, kita tidak bisa lagi hanya membicarakan ekstraksi nilai ekonomi dalam bentuk kekayaan mineral atau nilai lebih (surplus value). Kita juga harus membicarakan ekstraksi kekayaan ekologi dan kapasitas perawatan dari negara-negara pinggiran ke negara-negara inti kapitalis.
FF: Diskusi di kalangan kiri mengenai imperialisme sering merujuk pada buku Vladimir Lenin, seorang revolusioner Rusia, tentang topik ini. Seberapa relevan buku tersebut hari ini, dan apakah ada elemen yang telah digantikan oleh perkembangan selanjutnya?
NF: Analisis Lenin tentang imperialisme merupakan kontribusi yang sangat berharga dan berpengaruh pada masanya. Namun, sejak itu konsep imperialisme telah mengalami pengembangan dan pendalaman. Saya juga melihat adanya sejumlah persoalan dalam definisi awal yang dikemukakan Lenin.
Lenin secara khusus mengaitkan imperialisme dengan finansialisasi. Memang benar kita hidup di era finansialisasi yang luar biasa pesat. Namun, saya tidak sepenuhnya setuju bahwa finansialisasi per se bisa dijadikan penanda utama untuk mendefinisikan imperialisme. Imperialisme juga mencakup transfer kekayaan – baik yang telah dikapitalisasi maupun yang belum sepenuhnya dikapitalisasi, seperti kekayaan alam dan kerja-kerja perawatan. Lenin juga menggambarkan bahwa imperialisme sebagai tahap terakhir dari kapitalisme. Gagasan “tahap terakhir” ini mengingatkan pada pandangan Rosa Luxemburg bahwa pada suatu titik, kapitalisme akan merambah ke seluruh dunia dan tidak akan ada lagi wilayah “luar’’ yang bisa dieksploitasi. Pada titik itu, kapitalisme dianggap tidak akan mampu lagi berkembang dan akan runtuh. Namun kenyataannya, imperialisme hari ini mencakup tidak hanya melibatkan integrasi bentuk-bentuk nilai sosial baru ke dalam sirkuit reproduksi kapitalis, tetapi juga pengusiran dan eksklusi. Misalnya, pengusiran miliaran orang dari ekonomi resmi (formal) ke zona informal atau abu-abu, yang justru menjadi sumber ekstraksi nilai baru bagi kapital.
Selain itu, pola geografis dari transfer nilai kini tak lagi sejalan dengan peta lama antara Dunia Pertama, Dunia Kedua, dan Dunia Ketiga. Kita menyaksikan munculnya konfigurasi politik dan geografis baru, termasuk perpindahan basis industri dari negara-negara inti lama ke wilayah seperti BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Bahkan, beberapa bekas kekuatan kolonial seperti Portugal kini berada dalam posisi subordinat dalam kerangka Uni Eropa, tunduk pada kebijakan lembaga seperti Troika (IMF, Komisi Eropa, dan Bank Sentral Eropa). Untuk pertama kalinya, populasi di negara-negara Global Utara (Global North) juga mengalami kondisi serupa dengan yang sebelumnya hanya dialami oleh masyarakat pinggiran.
Jadi, bentuk-bentuk imperialisme yang kita hadapi kini jauh lebih kompleks, tidak lagi mengikuti garis pemisah kolonial klasik antara yang menjajah dan yang dijajah. Namun demikian, meskipun lanskapnya telah berubah, imperialisme tetap menjadi istilah paling tepat untuk memahami dan menjelaskan dinamika ini.
FF: Seperti yang Anda catat, pembahasan Marxis tentang imperialisme cenderung fokus secara ketat pada transfer nilai ekonomi. Namun, Anda menyoroti kebutuhan untuk mempertimbangkan transfer kekayaan alam dan kapasitas perawatan. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana transfer-transfer ini terjadi?
NF: Mari saya mulai dengan pembahasan ekonomi perawatan, atau apa yang oleh para feminis sebut sebagai kerja reproduksi sosial (social reproductive labour). Istilah ini berbeda dari ’’reproduksi sosial’’ dalam dari yang lebih umum, yang mencakup semua proses yang menopang kelangsungan suatu formasi/tatanan sosial.
Kerja reproduksi sosial merujuk secara khusus pada aktivitas-aktivitas yang memungkinkan pemulihan tenaga kerja sehari-hari dan regenerasi populasi tenaga kerja dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini mencakup aspek biologis seperti kelahiran, pekerjaan perawatan dan pengasuhan sehari-hari, serta proses sosialisasi yang membentuk individu sebagai anggota kelas tertentu dalam masyarakat tertentu. Historisnya, pekerjaan-pekerjaan ini dikaitkan dengan perempuan—meskipun laki-laki juga melakukan sebagian di antaranya. Dan sebagian besar pekerjaan ini, secara historis pula, berlangsung di luar wilayah ekonomi formal dalam masyarakat kapitalis. Kapitalisme secara khas memisahkan dengan tegas antara kerja upahan dan kerja reproduksi sosial (yang sering disebut sebagai kerja perawatan). Namun meskipun tidak dihitung sebagai bagian dari sektor formal, kerja perawatan ini sangat penting—karena ia menopang kerja upahan, memungkinkan akumulasi nilai lebih, dan menjadi fondasi bagi berjalannya sistem kapitalisme itu sendiri.
Kerja upahan tidak bisa berlangsung tanpa adanya berbagai bentuk kerja lain seperti pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, pendidikan, perawatan emosional, dan aktivitas-aktivitas lain yang memastikan keberlanjutan tenaga kerja—baik dalam memperbarui pekerja yang sudah ada maupun membesarkan generasi pekerja baru.
Secara historis, sistem kapitalis cenderung menganggap remeh fakta bahwa pasokan tenaga kerja akan selalu tersedia. Namun pada masa awal industrialisasi, dampaknya begitu drastis sehingga kehidupan keluarga menjadi hampir mustahil di banyak kota industri utama di negara-negara kapitalis inti. Kondisi ini menjadikan persoalan reproduksi sosial sebagai isu politik yang penting. Sebagai respons, negara-negara kaya yang memiliki sumber daya pajak yang cukup mulai membangun negara kesejahteraan, yang mengambil alih sebagian tanggung jawab kolektif dalam mendukung proses reproduksi sosial.
Salah satu cara yang digunakan negara-negara kaya untuk mengatasi kekurangan tenaga perawatan adalah dengan “mengimpor” pekerja perawatan murah dari negara-negara miskin. Agar perempuan di negara-negara maju bisa lebih bebas bekerja di sektor formal, maka pekerjaan reproduksi sosial—seperti mengasuh, merawat, dan membersihkan—perlu diperdagangkan sebagai jasa. Dampaknya, terjadi lonjakan migrasi perempuan dari negara-negara miskin yang datang untuk mengisi posisi sebagai pekerja perawatan berbayar.
Pemerintah di negara-negara miskin, yang sangat membutuhkan devisa, bahkan mendorong warganya untuk bermigrasi demi mendapatkan remitansi—yaitu uang yang dikirim balik ke keluarga di tanah air. Tapi ini menciptakan rantai beban baru: para migran perempuan itu harus menyerahkan pekerjaan perawatan di rumah mereka sendiri kepada perempuan lain yang lebih miskin, yang juga harus melakukan hal serupa, dan seterusnya. Hasilnya adalah pemindahan beban kekurangan perawatan dari keluarga kaya ke keluarga miskin, dan dari negara-negara di Global Utara ke negara-negara di Global Selatan.
Fenomena ini kini begitu meluas hingga dikaji sebagai bentuk baru dari imperialisme. Para feminis menyebutnya sebagai rantai perawatan global, istilah yang menggambarkan pola relasi global dalam kerja perawatan—sebuah permainan kata dari konsep rantai komoditas global yang lebih umum dikenal. Negara seperti Filipina menjadi contoh utama, di mana pemerintah sangat bergantung pada ekspor tenaga kerja perempuan di sektor perawatan ke tempat-tempat seperti Los Angeles, Israel, dan negara-negara Teluk. Saya merekomendasikan artikel dari Arlie Russell Hochschild, “Love and Gold”, di mana ia menjelaskan bagaimana cinta telah menjadi “emas baru”. Alih-alih mengekspor kekayaan mineral, negara-negara kini mengekspor komoditas yang telah dimonetisasi ini.
Hal serupa juga terjadi dalam hal kekayaan alam. Seperti halnya kerja reproduksi sosial, alam diperlakukan oleh kapital sebagai sumber daya yang bisa diambil secara gratis atau dengan biaya sangat rendah demi kepentingan akumulasi modal. Sejak awal kemunculannya, kapitalisme sangat bergantung pada pengambilan kekayaan alam—seperti perak, kapas, tembakau, gula, dan kakao—yang berperan penting dalam membentuk fondasi sistem kapitalis, bahkan sejak fase awal seperti kapitalisme merkantilis dan kapitalisme berbasis perbudakan. Selanjutnya, proses industrialisasi di kawasan seperti Eropa, Amerika Utara, dan Jepang tak lepas dari praktik ekstraktivisme di wilayah-wilayah pinggiran. Misalnya, kelancaran operasional pabrik-pabrik di Manchester sangat bergantung pada arus impor besar-besaran bahan mentah dari Amerika Selatan dan wilayah-wilayah kolonial lainnya.
Ekspor kekayaan alam bukanlah hal baru, namun kini fenomena ini berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks akibat krisis iklim. Kita semakin menyadari bahwa persoalannya bukan lagi sekadar soal mengalirnya sumber daya dari wilayah pinggiran ke pusat kapitalis, tetapi juga soal ekspor limbah dan dampak perubahan iklim ke wilayah-wilayah yang tereksploitasi. Pandangan lama tentang imperialisme sebagai proses mengambil yang “bermanfaat” dari satu tempat untuk dinikmati di tempat lain kini tidak lagi memadai. Kita juga harus memperhitungkan kemana limbah dari proses tersebut dibuang, serta siapa yang menanggung akibat dari produksi yang dianggap ‘baik’ itu. Tentu saja, anggapan bahwa dampak lingkungan bisa selamanya dialihkan ke tempat lain adalah keliru, mengingat sistem iklim bersifat global. Namun pada kenyataannya, komunitas-komunitas di wilayah pinggiran saat ini menanggung beban lingkungan global secara sangat tidak seimbang.
Inilah sebabnya mengapa konsep imperialisme ekologis menjadi sangat relevan dan penting. Beberapa kajian terbaru yang paling inovatif tentang imperialisme kini tidak hanya menyoroti rantai perawatan global, tetapi juga menekankan teori perpindahan beban ekologis dan bentuk pertukaran ekologis yang timpang. Ini bukan berarti meninggalkan fokus klasik pada ekstraksi nilai ekonomi, melainkan menambahkan dimensi bahwa analisis Marxian tentang imperialisme, secara tidak sengaja, telah mengadopsi cara pandang kapitalis tentang kekayaan—dan dengan begitu, melewatkan aspek-aspek penting lainnya yang juga menentukan.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
FF: Anda juga menggunakan konsep ekspropriasi, bersama dengan eksploitasi, saat menganalisis imperialisme. Dapatkah Anda menjelaskan apa yang Anda maksud dengan ini?
NF: Dalam teori Marxis klasik, eksploitasi merujuk pada situasi kerja upahan, di mana tenaga kerja dijual di pasar tenaga kerja dan pekerja hanya menerima upah untuk waktu kerja yang diperlukan (necessary labour time) tetapi tidak untuk waktu kerja lebih (surplus labour time). Dengan kata lain, upah hanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan memastikan regenerasi tenaga kerja—setidaknya secara teoritis. Eksploitasi, dalam konteks ini, merujuk pada perbedaan antara nilai total yang dihasilkan oleh pekerja dan jumlah upah yang mereka terima—nilai surplus yang diserap oleh pemilik modal.
Sementara itu, ekspropriasi, bila dikaitkan dengan tenaga kerja, menggambarkan situasi yang lebih ekstrem: tenaga kerja bahkan tidak mendapat bayaran untuk waktu kerja yang diperlukan. Sebelum era industrialisasi, akumulasi kapital banyak bergantung pada kerja paksa atau kerja tidak bebas, yang diperoleh melalui kekerasan dan perampasan. Ekspropriasi juga dapat berarti penyitaan paksa atas tanah, hewan ternak, atau bentuk kekayaan lainnya. Jadi, ketika saya menyebut ekspropriasi, yang dimaksud adalah perampasan kekayaan—baik berupa tenaga kerja, tanah, maupun aset lain—yang kemudian dimasukkan secara paksa ke dalam mekanisme akumulasi kapitalis. Gagasan ini sebenarnya bukan hal baru: Rosa Luxemburg pernah membahasnya, dan David Harvey mengembangkannya lebih lanjut melalui konsep “akumulasi melalui perampasan” (accumulation by dispossession).
Dalam tradisi Marxisme, sering muncul anggapan bahwa proses akumulasi kapital terutama berlangsung melalui eksploitasi tenaga kerja. Namun, ekspropriasi sebenarnya selalu menjadi bagian penting dari dinamika kapitalisme—dan masih berlangsung hingga saat ini. Ekspropriasi bukan sekadar ciri khas tahap awal sistem kapitalis, melainkan elemen struktural yang terus melekat dalam cara kerja kapitalisme, sejajar dengan eksploitasi. Kapitalisme tidak bisa terus menumpuk modal hanya dengan mengandalkan eksploitasi tenaga kerja bebas di pabrik-pabrik yang diberi upah sekadar cukup untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Ada batasnya. Karena itu, sistem juga sangat bergantung pada perampasan—baik tenaga kerja yang tidak dibayar maupun sumber daya alam—sebagai cara lain untuk meningkatkan keuntungan.
Dengan kata lain, ekspropriasi menjadi fondasi yang menopang eksploitasi. Tanpa perampasan yang terus-menerus atas kekayaan dan tenaga kerja, proses eksploitasi kapitalis tidak akan bisa bertahan.
FF: Bagaimana perampasan berbeda dari super-eksploitasi, yang juga merujuk pada tenaga kerja yang dibayar kurang dari waktu kerja yang diperlukan?
NF: Istilah super-eksploitasi sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana pekerja kulit berwarna menerima upah yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja kulit putih, sehingga mengalami tingkat eksploitasi yang lebih parah. Saya tidak mengatakan pendekatan ini keliru, tetapi menurut saya ia terlalu menekankan aspek ekonomi secara sempit. Ekspropriasi tenaga kerja tidak hanya soal pengambilan nilai lebih, melainkan juga berkaitan dengan status sosial, struktur hierarki, dan bentuk-bentuk paksaan serta kekerasan yang dijalankan terhadap kelompok tertentu—termasuk penghinaan, peminggiran, dan tekanan sistemik yang berlangsung dalam intensitas yang berbeda-beda. Ekspropriasi bukan semata-mata mekanisme ekonomi, tapi juga dijalankan melalui cara-cara politik dan koersif. Bahkan di negara seperti Amerika Serikat, pekerja kulit berwarna menghadapi pemaksaan kerja di penjara, intimidasi dari aparat kepolisian, kekerasan fisik, bahkan pembunuhan, serta berbagai bentuk pelecehan dan perendahan martabat. Semua ini bukan fenomena terpisah dari akumulasi kapital, melainkan bagian darinya. Karena itu, saya memandang bahwa kategori super-eksploitasi terlalu membatasi masalah ini dalam kerangka ekonomi saja.
Saya ingin menambahkan, secara historis, pembagian antara eksploitasi dan ekspropriasi juga sering kali berjalan seiring dengan garis rasial global. Populasi Eropa, setelah melalui masa-masa ekspropriasi di awal sejarah kapitalisme, kemudian berperan sebagai kelas pekerja yang dieksploitasi melalui kerja upahan. Sementara itu, komunitas kulit berwarna di koloni dan wilayah pinggiran terus mengalami ekspropriasi yang berkelanjutan. Eksploitasi yang terjadi di pusat-pusat kapitalisme tidak bisa dipahami secara utuh tanpa melihat kaitannya dengan ekspropriasi yang terjadi di wilayah-wilayah pinggiran.
Pemikir Marxis kulit hitam seperti W.E.B. Du Bois dalam karya besarnya Black Reconstruction menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap kelas pekerja industri kulit putih di Eropa dan Amerika Utara berlangsung secara bersamaan dan saling bergantung dengan ekspropriasi terhadap pekerja budak kulit hitam.
FF: Seberapa besar peran mekanisme ekspropriasi dan eksploitasi imperialis saat ini dibandingkan dengan masa lalu?
NF: Ekspropriasi dan eksploitasi sama-sama memainkan peran penting dalam proses akumulasi modal sepanjang sejarah perkembangan kapitalisme, meskipun dengan cara yang berbeda. Saya tertarik untuk menelusuri bagaimana hubungan antara kedua proses ini berkembang secara historis, serta bagaimana bentuk dan peran relatif masing-masing berubah dari satu fase kapitalisme ke fase berikutnya.
Sebagai contoh, dalam fase kapitalisme yang ditandai oleh dominasi sektor keuangan saat ini, utang telah menjadi salah satu instrumen utama dalam ekstraksi imperial. Lembaga-lembaga keuangan global menggunakan mekanisme utang untuk memaksa negara-negara mengurangi pengeluaran sosial, menerapkan kebijakan penghematan (austerity), dan bekerja sama dengan investor dalam pengambilan nilai dari masyarakat. Utang juga menjadi alat untuk merampas tanah dari petani di Selatan Global, memungkinkan korporasi menguasai sumber daya strategis seperti energi, air, lahan pertanian, dan bahkan proyek carbon offset. Selain itu, utang memainkan peran sentral dalam proses akumulasi modal di pusat-pusat kapitalisme. Pekerja sektor jasa yang hidup dalam kondisi kerja tidak tetap dan menerima upah di bawah standar kebutuhan reproduksi sosial kini dipaksa mengandalkan kredit konsumen untuk bertahan hidup—sebuah bentuk ekspropriasi yang berlangsung secara halus namun sistemik.
Di berbagai level dan wilayah, utang telah menjadi pendorong utama gelombang baru penguasaan sumber daya secara besar-besaran. Fenomena ini melahirkan bentuk-bentuk pengambilalihan dan eksploitasi yang baru dan bersifat campuran (hibrida). Contohnya, banyak pekerja bergaji di negara-negara pascakolonial secara formal dianggap bebas, tetapi mereka hidup dalam kondisi di mana utang negara yang sangat besar menyebabkan sebagian besar tenaga kerja nasional diarahkan untuk membayar utang tersebut. Situasi serupa juga muncul di negara-negara kaya, di mana peningkatan tajam utang konsumen dalam era neoliberalisme telah menciptakan kondisi di mana pekerja—yang sebelumnya hanya mengalami eksploitasi—kini juga terjebak dalam ekspropriasi finansial melalui kredit, pinjaman, dan utang pribadi.
Bentuk-bentuk baru ini mengaburkan batas tradisional antara pekerja kulit hitam yang dulu diperbudak dan dieksploitasi secara brutal, dan pekerja kulit putih yang dieksploitasi namun tetap dianggap bebas. Kini, garis pemisah itu menjadi jauh lebih kompleks dan tidak lagi mudah dipetakan. Namun, kondisi ini bukan berarti bahwa imperialisme telah berakhir—justru menunjukkan bahwa pola relasi kekuasaan dan penindasan global telah menjadi lebih rumit dan membutuhkan analisis yang lebih tajam.
FF: Kekuatan imperialis awal membangun kekayaan dan kekuatan militer mereka melalui penaklukan kolonial dan penjarahan masyarakat pra-kapitalis. Apakah ada kekuatan imperialis baru yang muncul sejak itu? Dan jika ya, apa dasar ekonomi dari kekuatan-kekuatan baru ini?
NF: Walaupun saya tidak akan membahas secara tuntas apakah negara-negara sosialis yang pernah ada bisa disebut sebagai imperialis—karena itu merupakan persoalan yang kompleks—saya tidak ragu bahwa beberapa negara pasca-Komunis memang bersifat imperialis.
China adalah contoh yang paling mencolok. Menurut saya, istilah imperialisme sangat tepat untuk menggambarkan praktik ekstraktivisme yang dilakukan China di benua Afrika. Ini tetap berlaku meskipun pendekatan China berbeda dari model kolonialisme langsung yang dulu dijalankan oleh perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat atau Eropa. Dalam kasus China, kita tidak melihat penaklukan militer atau eksploitasi kolonial dalam bentuk klasik.
FF: Mengingat apa yang terjadi dalam kapitalisme yang terfinansialisasi, apakah perusahaan transnasional kini dapat beroperasi dengan sukses tanpa akar institusional di negara imperialis?
NF: Finansialisasi telah mengubah keseimbangan kekuasaan antara negara dan korporasi, dengan hasil bahwa korporasi kini memiliki pengaruh yang jauh lebih besar, sementara negara—bahkan negara-negara yang kuat—mengalami penurunan kendali. Saat ini, kita menyaksikan kemunculan korporasi global raksasa yang kekayaannya sering kali melampaui kekayaan banyak negara berdaulat. Korporasi-korporasi ini beroperasi di luar jangkauan otoritas negara, sering bermarkas di yurisdiksi bebas pajak seperti Andorra, dan tidak lagi terikat kuat pada negara kapitalis tempat mereka bermula. Mereka bahkan mampu menantang otoritas negara seperti Amerika Serikat, yang meskipun secara formal masih menjadi kekuatan hegemonik global, jelas sedang mengalami penurunan. Negara AS, misalnya, tidak memiliki kendali langsung atas raksasa seperti Apple atau Google. Kita tidak lagi berada dalam era di mana perusahaan besar secara jelas berfungsi sebagai “juara nasional” yang dilindungi dan didorong oleh negara-bangsa. Konstelasi kekuasaan ekonomi saat ini jauh lebih kompleks dan tidak terikat pada batas-batas nasional seperti sebelumnya.
Meski begitu, menurut saya masih terlalu dini untuk menyimpulkan secara tegas bahwa perusahaan transnasional bisa sepenuhnya beroperasi tanpa dukungan institusional dari kekuatan-kekuatan imperialis. Amerika Serikat, misalnya, masih memiliki pengaruh besar melalui dominasi dolar AS sebagai mata uang global, sistem perbankan internasional, dan infrastruktur keuangan dunia. Selain itu, hukum properti AS telah menjelma menjadi standar hukum global melalui perjanjian seperti Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang mengatur hak kekayaan intelektual.
Katharina Pistor, dalam bukunya The Code of Capital, menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hukum AS—termasuk hukum kontrak, hak milik, dan penyelesaian sengketa—telah diekspor dan diadopsi secara global, menjadi semacam perpanjangan dari kekuasaan hukum Amerika, meskipun tidak selalu secara langsung dari negara itu sendiri. Tapi apakah ini berarti pemerintah AS memiliki kendali penuh atas korporasi-korporasi tersebut, seperti Apple, adalah persoalan lain yang lebih rumit.
FF: Bagaimana kita memahami persaingan AS-China yang semakin intensif mengingat kedua ekonomi tersebut lebih terintegrasi daripada sebelumnya? Dan bagaimana Anda memandang dinamika saat ini dalam kapitalisme global mengingat bukan hanya kekuatan imperialis tradisional seperti AS dan Israel yang melancarkan perang skala besar, tetapi juga Rusia, bahkan Turki dan Arab Saudi, yang menggunakan kekuatan militer di luar perbatasan mereka?
NF: Terdapat banyak ujian yang sedang dihadapi AS. Secara militer, Amerika Serikat masih merupakan kekuatan besar, meskipun bukan satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir. Namun, dari sisi ekonomi, situasinya lebih kompleks—tidak sepenuhnya kuat, tapi juga belum runtuh. Sementara itu, secara moral, posisi dan kredibilitas global AS telah mengalami kemunduran yang cukup serius.
Terkait perang Israel di Gaza, sebagai seorang Yahudi Amerika, saya pribadi merasa sangat marah karena AS tidak menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan konflik tersebut. Padahal, AS memiliki kekuatan besar atas Israel—cukup dengan menghentikan dukungan, sebenarnya bisa memberi tekanan. Namun, pengaruh ini tidak berlaku di semua konteks global.
Contohnya, kita melihat China muncul sebagai kekuatan ekonomi utama yang mulai memikirkan bagaimana dan kapan mereka akan mengambil peran lebih besar di panggung global. China tampak siap menjadi kekuatan besar, tetapi masih mempertimbangkan langkah strategis berikutnya. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah China akan menggantikan AS sebagai kekuatan hegemonik baru, atau justru kita akan memasuki era dunia multipolar yang lebih kompleks?
Di sisi lain, Rusia, meskipun secara kekuatan ekonomi dan militer tergolong menurun, tetap mampu memainkan peran geopolitik yang signifikan. Terlepas dari penilaian pribadi terhadap Putin, dia berhasil memperluas pengaruh Rusia jauh melampaui kekuatan riilnya—tidak hanya di wilayah sekitar Rusia, tetapi juga di Suriah, Afrika, dan berbagai kawasan lainnya. Bersama China, Rusia, Iran, Turki, dan beberapa negara lain, muncul blok tandingan terhadap dominasi AS. Sementara itu, Uni Eropa justru gagal tampil sebagai kekuatan politik global yang solid, karena berbagai kendala seperti fragmentasi internal dan struktur kelembagaan yang rumit.
Seperti yang Anda katakan, ekonomi AS dan China saling terhubung erat, dan hal ini justru memperlambat proses pergeseran kekuatan global. Namun, ada juga faktor yang sulit diprediksi, seperti kembalinya Trump sebagai Presiden AS, yang menjalankan kebijakan ekonomi yang lebih proteksionis seperti tarif dagang baru, atau bahkan ketegangan militer. Meski begitu, Trump dengan pendekatan isolasionis “America First”-nya terkadang justru lebih rasional dalam urusan luar negeri dibandingkan para elite kebijakan luar negeri arus utama.
Bagaimanapun juga, kita sedang menuju masa yang penuh ketidakpastian. Ketidakhadiran kekuatan hegemonik yang stabil adalah alasan yang sah untuk merasa cemas. Amerika Serikat tampak kehilangan arah dan tidak punya strategi yang jelas. Dalam situasi seperti ini, risiko bahwa AS akan mengambil tindakan yang sembrono sangatlah tinggi. Singkatnya, kita berada di masa yang berbahaya.
FF: Apakah Anda melihat kemungkinan untuk membangun jembatan antara perjuangan anti-imperialis? Secara umum, mengingat apa yang telah kita bahas, bagaimana bentuk anti-imperialisme dan internasionalisme anti-kapitalis abad ke-21?
NF: Ada kemungkinan, tetapi seberapa besar kemungkinan itu terwujud adalah pertanyaan lain.
Seperti yang saya katakan, kita kini hidup di zaman yang penuh resiko. Kita bisa saja tergelincir ke dalam perang nuklir atau perang dunia yang mengerikan kapan saja. Kita menghadapi krisis ekologi yang mengancam kelangsungan hidup planet ini. Dan ada ketidakpastian dan ketidakamanan yang luar biasa dalam hal penghidupan, bahkan di bagian dunia yang kaya.
Di tengah situasi krisis yang ekstrem ini, di mana kepastian-kepastian normal telah runtuh, banyak orang bersedia mempertimbangkan kembali apa yang secara politik mungkin dilakukan. Hal ini telah membuka ruang bagi kekuatan kiri yang bersedia memikirkan jenis aliansi baru yang kita butuhkan untuk zaman ini. Namun, pada saat yang sama, kita juga menyaksikan munculnya populisme kanan—dan dalam beberapa kasus, proto-fasis atau setidaknya otoriter. Semua ini adalah respons terhadap keruntuhan hegemoni borjuis (dalam arti Gramscian, bukan geopolitik).
Saya telah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sejak Krisis Ekonomi Global 2008 dan Gerakan Occupy pada 2011. Kadang-kadang saya merasa optimis tentang prospek kiri emansipatoris untuk membangun aliansi anti-kapitalis dan anti-imperialis. Pada saat lain, sepertinya sayap kanan jauh lebih berhasil dalam mengarahkan ketidakpuasan. Namun, intinya adalah kita tidak memiliki pilihan lain selain berjuang untuk internasionalisme anti-imperialis dan anti-kapitalis yang baru—yang feminis, anti-rasis, demokratis, dan hijau. Semua kata sifat ini menunjuk pada kekhawatiran eksistensial yang sah dari orang-orang yang bergerak. Kita tidak dalam posisi untuk mengatakan, misalnya, bahwa perjuangan melawan kekerasan polisi kurang penting dibandingkan dengan perjuangan melawan perubahan iklim: bagi mereka yang mengalami kekerasan polisi, tidak ada yang lebih penting.
Hal yang masih memberi saya secercah harapan adalah fakta bahwa berbagai krisis ini sebenarnya bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Semuanya memiliki akar yang sama, yang saya sebut sebagai kapitalisme kanibal dalam buku terbaru saya. Saya berargumen bahwa kapitalisme memiliki kecenderungan struktural untuk melahap segala hal: alam, kerja perawatan, kekayaan kolektif masyarakat tertindas, serta energi dan kreativitas para pekerja.
Jika kita bisa membantu lebih banyak orang memahami hubungan ini, maka gagasan dan upaya untuk membangun aliansi yang lebih luas akan mulai masuk akal. Tantangannya adalah menemukan cara menyatukan semua bentuk perjuangan ini tanpa menciptakan hirarki penindasan. Karena pada akhirnya, tidak ada satu gerakan pun yang cukup kuat untuk mengubah dunia sendirian.***